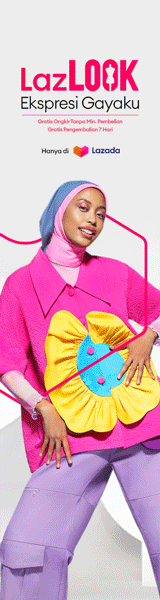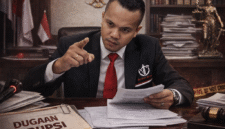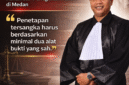Medan // krimsusnewstv.id — Tahun 2025 semestinya menjadi etalase kemajuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun di Sumatera Utara, potret pelayanan kesehatan masih menyisakan persoalan mendasar: antrean panjang, rujukan berlapis, dan kegamangan fasilitas layanan dalam menangani pasien peserta JKN. Di balik jargon Universal Health Coverage (UHC), pengalaman warga justru memperlihatkan jarak antara klaim kebijakan dan praktik di lapangan. minggu, 21/12/2025
Secara administratif, Sumatera Utara mencatat capaian kepesertaan JKN yang relatif tinggi. Pemerintah daerah kerap memamerkan angka di atas 90 persen sebagai indikator keberhasilan. Namun kepesertaan tidak otomatis bermakna akses. Banyak warga telah terdaftar, tetapi tetap tersisih ketika berhadapan dengan layanan kesehatan yang lamban, selektif, dan kerap defensif terhadap pasien BPJS Kesehatan.
Masalah paling nyata terlihat di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Ruang yang seharusnya menjadi pintu penyelamat justru kerap berubah menjadi arena negosiasi administratif. Pasien datang dalam kondisi darurat, namun disambut pertanyaan soal status kepesertaan, rujukan, hingga kelas BPJS. Di sejumlah rumah sakit kabupaten dan kota di Sumatera Utara, praktik “skrining kegawatdaruratan” sering kali menjadi bentuk penolakan halus. Ketika pasien masih bisa berbicara atau berjalan, kegawatdaruratannya diperdebatkan—bukan ditangani.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini mencerminkan kegagalan memahami prinsip dasar layanan kesehatan: keselamatan pasien harus didahulukan dari logika klaim. Dalam banyak kasus, keputusan medis dibayangi kekhawatiran rumah sakit terhadap klaim BPJS yang dinilai rumit, lambat, atau berisiko tidak dibayar. Akibatnya, IGD bekerja setengah hati—terjepit antara sumpah profesi dan kecemasan finansial institusi.
Persoalan serupa muncul pada layanan penunjang seperti radiologi dan laboratorium. Waktu tunggu pemeriksaan bagi pasien JKN kerap lebih lama dibanding pasien umum. Alasan klasik pun berulang: alat terbatas, petugas tidak tersedia, atau jadwal penuh. Dalam praktik, keterlambatan ini bukan semata soal teknis, melainkan cermin sistem yang masih memandang pasien JKN sebagai beban, bukan subjek pelayanan.
Sistem rujukan berjenjang turut memperumit keadaan. Di atas kertas, mekanisme ini dirancang untuk efisiensi. Di lapangan, ia sering berubah menjadi labirin. Pasien dari wilayah terpencil seperti Nias, Mandailing Natal, atau Tapanuli harus berputar dari faskes pertama ke rumah sakit rujukan, hanya untuk kembali ditolak dengan alasan kapasitas penuh atau layanan tidak tersedia. Pada akhirnya, keluarga dipaksa memilih: menunggu dengan risiko kondisi memburuk, atau membayar mandiri demi kecepatan layanan.
Berbagai persoalan ini menyingkap fakta yang kerap dihindari: jaminan kesehatan masih berfokus pada pengelolaan kepesertaan, belum pada kualitas layanan. Negara sibuk menghitung angka cakupan, tetapi lalai memastikan kesiapan fasilitas, tenaga medis, serta mekanisme pembiayaan yang adil bagi rumah sakit. BPJS Kesehatan sebagai operator sistem juga belum sepenuhnya mampu meredakan ketegangan struktural antara kendali biaya dan kebutuhan klinis.
Rekomendasi kebijakan perlu diarahkan secara tegas. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus berhenti menjadikan UHC sekadar slogan statistik. Audit layanan IGD dan layanan penunjang perlu dilakukan secara terbuka, disertai sanksi nyata bagi fasilitas yang menolak pasien darurat. Di saat yang sama, mekanisme klaim BPJS harus disederhanakan dan dipercepat agar rumah sakit tidak terus-menerus menjadikan pasien sebagai korban ketakutan administratif.
Tanpa pembenahan serius, jaminan kesehatan hanya akan menjadi kartu keanggotaan tanpa makna. Jika IGD dibiarkan menjadi ruang tawar-menawar, radiologi menjadi antrean tanpa kepastian, dan rujukan menjadi jalan memutar penderitaan, maka satu hal patut ditegaskan: yang darurat bukan lagi kondisi pasien, melainkan reformasi sistem jaminan kesehatan itu sendiri.
Penulis : Tim/red
Editor : Redaksi